Bulan
sabit di penghujung November menjadi saksi ketika Marjikun mengecek seberapa
panjang nyawanya dalam besaran rupiah. Kedua tangan lelaki itu sibuk merazia
kantong-kantong pakaian, termasuk saku-saku sempit celana jinsnya. Tak ada yang
cukup menggembirakan selain satu lembar pecahan seratus ribunya.
“Aku
masih bisa hidup untuk dua hari lagi,” ujarnya sambil menahan gereget diri,
“Atau bahkan tiga hari atau seminggu lagi.”
Ia
mendadak menunduk, tak benar-benar menatap seberapa rapi seseorang mengatur
paving blok.
“Tapi
itu uang haram! Seharusnya sudah lama aku lepas profesi menjijikan itu!”
Jujur
saja pada dunia, jika Marjikun tengah terperangkap nasib.
“Nasib
bisa diubah dengan doa dan usaha, bung!”
Marjikun
terpaksa meladeni gusaran hati sendiri. Dan ini bukan yang pertama. Sudah masuk
bulan ke dua sejak untuk pertama kalinya ia mendapatkan pengalaman berharga jika
kehilangan harta dari mencopet, itu begitu membawa perasaan. Jejak-jejak
penyesalan membuntutinya kemana pun ia pergi.
Seorang
anak lelaki dengan potongan rambut plontos datang menghampiri. Ia mengusik
kesendirian Marjikun.
“Bapak,
kata ibu disuruh pulang. Mie rebus pesanan bapak sudah lama dibikin, sekarang sudah
dingin. Kalau bapak mau nanti ibu buatkan yang baru tapi tanpa telor kali ini.”
Marjikun
menahan degupan, datangnya dari kegeraman yang sudah terlalu lama bersarang di
hati. Marjikun sudah lama sukses berdrama, seakan ia adalah lelaki terhormat
dengan pekerjaan terhormat. Malam itu ia semakin menambah bobot kesuksesan itu.
Di
rumah, usai menyantap menu mie pengganti, tidak serta-merta menenangkan hati
Marjikun. Di sana bahkan ada kehangatan orang-orang terdekat, yang itu juga
belum sanggup melenyapkan keresahan hatinya. Sedari awal, jauh sebelum ia
menikah dan punya anak, Marjikun sudah menyadari jika akan ada saatnya seorang
lelaki mulai memerhatikan darimana ia mendapatkan uang.
Katakan
saja pada dunia, jika sebelumnya Marjikun sudah pernah mencoba mendapatkan
pekerjaan yang baik, tapi banyak lelaki lain di luar sana melakukan usaha yang
sama, bahkan jauh lebih hebat dari Marjikun.
Marjikun kalah saingan.
Jika
begitu katakan saja pada dunia jika Marjikun ingin melepas profesi mencopet
itu. Sesegera mungkin.
“Itu
mustahil! Sudah dua bulan aku memikirkannya tapi aku tak kunjung mendapatkan
jawaban. Pikiranku butek! Jangan salahkan aku jika esok hari, aku kembali
melakukan operasi rutin!”
Jika Marjikun
terjebak dilema, paling tidak lelaki itu tidak harus buru-buru kembali
mencopet. Bukankah masih ada sedikit napas kehidupan dalam selembar uang di dompet?
“Tentu
saja, aku dan keluargaku masih bisa hidup paling tidak dua hari lagi, kecuali...”
Istri Marjikun
datang membawa setoples rangginang. Marjikun melirik kepada toples itu. Seharusnya
rangginang itu hadir bersamaan semangkuk mie kuah panas tadi. Tapi tak apalah,
cacat momen baginya sudah biasa, tidak di rumah tidak di medan operasi.
“Rangginangnya,
Pak?”
“Tentu
saja, Bu.”
Walau
dipikirnya telat, tapi itu bukan berarti ia enggan menyantap rangginang itu.
Marjikun mencomot satu.
“Hem..
gurih Bu.”
Istri Marjikun
tersenyum kecut. Mudah bagi Marjikun menghabiskan satu rangginang dan ia tak
tahan untuk mengambil satu yang lain. Istri Marjikun semakin tersenyum kecut.
“Pak...”
“Iya
bu.”
“Itu
rangginang pemberian tetangga Pak, katanya oleh-oleh kerabat dari Cianjur,
rangginang terasi buatan sendiri.”
“Pantas
enak, Bu! Baru kali ini aku makan rangginang senikmat ini! Jika saja tadi
datangnya bareng santap makan malamku, bisa tambah enak saja rasanya!”
“Maaf
pak tadi ibu lupa.”
Marjikun
seketika memaklumi. Marjikun mengambil rangginang ketiga. Ia merasa akan punya
waktu banyak untuk menghabiskan sisa beberapa potong lagi di dalam toples.
“Oh iya
pak, maafkan ibu, ibu juga lupa kalau Si Buyung sudah harus bayar SPP, bahkan
sudah nunggak dua bulan.”
“Uhuk!”
“Duh,
kenapa Pak?”
“Minta
air, Bu. Tolong.”
Marjikun
mulai tersadarkan jika selain setoples rangginang, istrinya juga membawa serta sepaket
beban hidup keluarga. Itu tidak bisa dipungkiri.
Marjikun
sudah banyak menelan pengalaman serupa jika perencanaan tidak selalu berakhir
mulus.
“Ini ada
sedikit, bisa ibu gunakan untuk keperluan tadi.”
Marjikun
harus bangun pagi. Ia sudah siap kembali ke medan operasi tidak lebih dari jam
tujuh pagi di halte Rawa Becek.
Di pagi
yang baru, Marjikun kembali berseragam. Hebatlah lelaki ini, punya dua seragam
untuk bangunan dusta yang berhasil ia jaga berpuluh tahun di hadapan istri,
tiga anaknya, dan segenap tetangga.
Jujurlah
pada dunia, jika Marjikun tidak seelegan yang dipikirkan orang.
“Diam
kau! Aku masih butuh kamuflase ini!”
Marjikun
selama ini merasa aman bersembunyi di balik profesi fiktifnya: makelar kartu
kredit. Ia seharusnya bisa mengarang peran yang lebih elegan. Otak mantan
mahasiswa jurusan ekonomi ini seharusnya berani mengaku sebagai pialang saham,
konsultan bisnis, atau auditor pajak.
“Tapi
nyatanya, itu dusta terbaikku! Orang rumah semua percaya tanpa syarat! Jadi
mulai sekarang, tolong diam dulu kamu! Aku nyaris sampai di tempat operasi!”
Di halte
Rawa Becek, Marjikun membaur bersama para penunggu angkutan bus. Berkali-kali
bus berhenti untuk mengabil penumpang, tapi Marjikun tahu bus mana yang ideal
dari yang paling ideal. Pengalaman mengatakan ikan besar berada di antara
penumpang multi status, syukur-syukur mendapatkan bus dengan penumpang dominan
pekerja. Ia sangat menghindari
penumpang dominan anak sekolahan. Ia pun tahu bus mana saja pemilik
mangsa terempuk. Satu di antaranya bus jurusan Tanah None, bus dominan warna
merah itu punya prestasi baik di mata seorang pencopet seperti dirinya. Itu bus
dengan lima bintang. Selalu menjanjikan.
“Tidak
ikut naik, Pak?” sahut kondektur dari muka pintu belakang.
Marjikun
sekali lagi memerhatikan lebih lekat ke dalam. Ia punya waktu kurang dari lima
detik untuk memutuskan apakah ia akan naik atau kembali menunggu bus incaran
lain.
“Selalu
ada celah di dalam kok, Pak!”
“Tidak!”
Akhirnya
Marjikun memutuskan untuk menunggu bus incaran lain.
“Aneh, kemana
para eksekutif muda itu?”
Jujurlah
pada dunia, jika Marjikun sudah kehilangan kemujuran masa lalu.
“Ini
wajar. Tak selalu mudah mencari rejeki, bukan? Aku masih bersedia bersabar untuk
menanti kedatangan bus selanjutnya.”
Jujurlah
pada dunia, jika Marjikun sudah sulit mencari rejeki dari bagian yang haram.
“Memang
mencopet itu pekerjaan haram, tapi paling tidak aku sudah melakukan sesuatu.
Aku bangun pagi, sarapan dan berpakaian layak. Berangkat kerja dengan semangat
jika masa depan ada dalam genggaman. Itu jauh lebih baik ketimbang lelaki yang
menghabiskan hidupnya di atas kasur dan kemalasan.”
Banyak
bus melintas di depannya, halte itu juga sudah banyak mengirimkan orang untuk
menjadi penumpang, tapi berjam-jam lamanya Marjikun masih tetap bertahan di
sana.
Jujurlah
pada dunia, jika Marjikun hanya menghabiskan waktu sia-sia. Jika Marjikun mau untuk
lebih sedikit lagi berusaha mencari pekerjaan tanpa harus membangun dusta,
mungkin Tuhan akan menjauhkan Marjikun dari bukan hanya kesia-siaan waktu, tapi
juga kesia-siaan hidup seutuhnya.
“Tuhan
telah lama meninggalkanku! Istriku rajin berdialog dengan-Nya tapi Dia tetap
diam di atas singgasana yang pernah dapat aku jangkau pada bagian
terrendahnya!”
Jujurlah
pada dunia, jika Marjikun tengah kalut berat, logika diseret ke sudut terpelik.
“Itulah
yang terjadi! Itu pula yang menyebabkan dialog ini terjadi karena kamu
sebelumnya tidak pernah muncul, menyapa, dan terasa begitu nyata!”
Jujurlah
pada diri sendiri, jika Marjikun mulai menghadapi satu fase baru kehidupan. Perhatikan
wahai Marjikun, berapa bilangan yang keluar mewakili umurmu kini?
“Nyaris
empat puluh tahun. Memangnya kenapa?”
Tak
tahukan engkau wahai Marjikun nasihat lama yang pernah engkau dengar semasa
kecil dulu, ketika dunia ini masih berwarna hitam dan putih, warna abu-abu
belum kau tahu saat itu. Nasihat lama tentang umur seorang lelaki.
“Sudah lama
aku meninggalkan masa lalu. Sudah lama aku tak baca buku, tak mengindahkan
nasihat dan peringatan, termasuk tentang umur lelaki yang sekarang kamu coba peringatkan
aku!”
Masih
ingatkan engkau wahai Marjikun,...
“Berhenti
di sana. Aku kedatangan bus hijau, tak kurang menjanjikan dengan bus merah
sialan itu!”
Bus
dengan dominan hijau menepi dan berusaha berhenti di posisi Marjikun berdiri
melambaikan tangan. Sang sopir berkenan memberikan pintu belakang bus itu untuk
Marjikun. Tapi Marjikun lagi-lagi dikecewakan. Tak ada ikan besar di bus hijau.
Kemana para pekerja kantoran itu?
Marjikun
nyaris membatalkan niat, tapi setelah ditengoknya ke belakang, sialnya tak ada
orang lain di halte itu. Memaksakan mengurungkan niat, supir dan kundektur akan
memasukan namanya ke dalam daftar hitam para penumpang bermasalah, jika bukan
copet apa lagi?
Marjikun
terpaksa naik bus itu. Ia berharap sang kundektur yang berada di pintu depan
tidak lekas menarikinya ongkos. Sepeser pun tak bersamanya.
Jika
saja mau sedikit lebih jujur dan logis, tak ada yang bisa menjamin itu wahai Marjikun.
“Aku
harap ada karena aku tak mau dipermalukan seisi bus sebagai lelaki lemah tak
punya ongkos bayar bus.”
Jika
saja Marjikun ingat, doa bisa mengambil perannya di saat-saat genting seperti
ini.
“Aku
harap seseorang menuntunku dalam berdoa, biar aku terlepas dari ancaman tak
terduga ini.”
Jika
saja Marjikun mau kembali meralat ucapnya tentang Tuhan dan mulai kembali
mengingat pelajaran masa lalu.
“Aku
mau! Aku ralat semua ucapanku tentang Tuhan. Tuhan tidak meninggalkanku jika aku
bertahan dengan kesabaranku. Tuhan berada di atas singgasana dalan keagunganNya.
Doa yang tulus, layaknya doa seorang Siti Hajar sanggup menggetarkan singgasanaNya.
Aku memohon yang sama!”
Bus tetap
melaju, memberi banyak waktu tambahan bagi Marjikun untuk menyempurnakan
permohonannya.
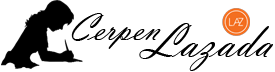







0 comments:
Post a Comment